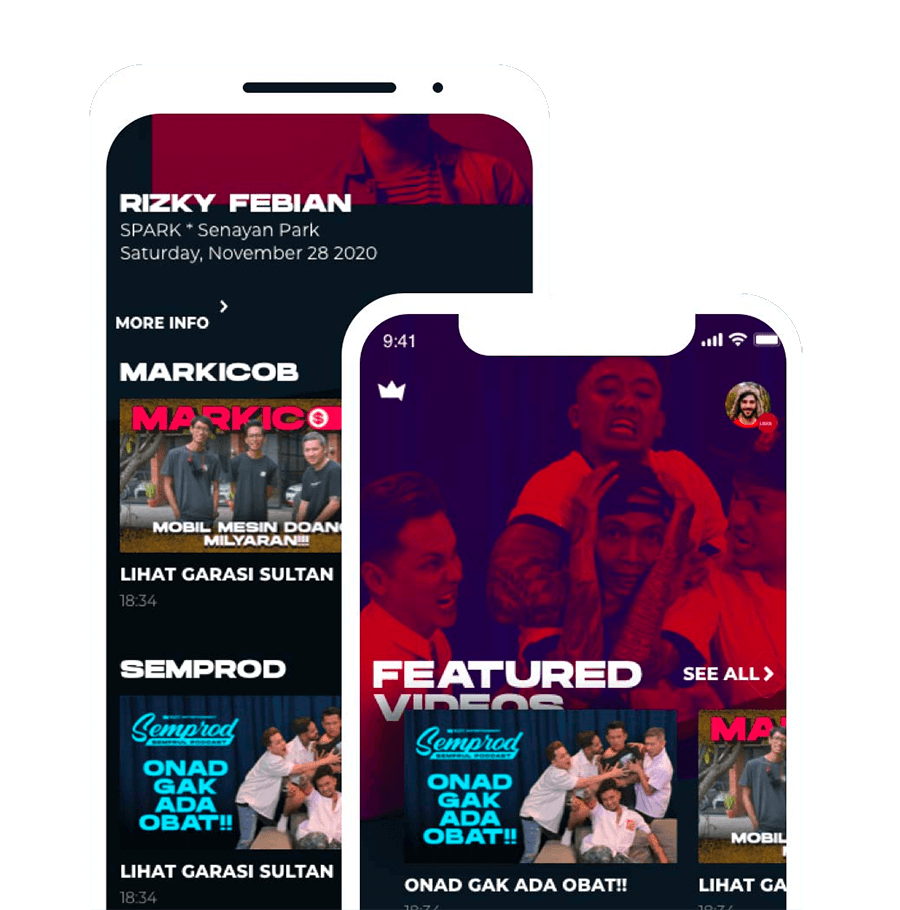Kapan punya pacar?
Kapan nikah?
Kapan punya anak?
Kok punya anak cuma 1 sih? Kapan dikasih adik?
Nye nye nyeee….
Tiap lo kemana-mana ketemu temen lama, keluarga jauh, atau tetangga julid pasti pertanyaan-pertanyaan di atas selalu lo temui di mana-mana. Kalo lo lagi jomblo nanti ditanya kapan punya pacar? Dan pertanyaan berlanjut sampe kapan punya cucu?
Kita sebut siklus pacaran - menikah - punya anak sebagai ‘relationship timeline’. Nah pertanyaannya adalah, apakah relationship timeline ini cocok buat semua orang?
Kalo kita nonton film atau baca buku atau ngeliat lingkungan sekitar kita, kayanya menikah dan berkeluarga adalah sebuah mandatory. Timeline kaya gini udah ada selama beberapa generasi, tapi di jaman sekarang apakah benar-benar dibutuhkan lagi?

Apakah relationship timeline harus diikuti semua hubungan?
Kalo diliat dari kacamata luar atau orang umum, hubungan yang ideal adalah mereka yang pacaran, terus nikah, terus punya anak dan berkeluarga. Yep, itu adalah hubungan yang sangat sangat sangat normal.
Tapi bukan berarti hal yang WAJIB dilakukan semua orang.

Seorang pekerja sosial bersertifikat, Sarah Brock Chávez, bilang kalo seharusnya ekspektasi buat ngikutin timeline ini udah nggak terjadi lagi. Hal kaya gini tuh udah kuno.
Chavez juga bilang lagi, “setiap individu dalam suatu hubungan punya kebutuhan dan tujuan yang berbeda, mereka juga punya sejarah hubungannya masing-masing. Jadi, setiap hubungan harus mengikuti timelinenya sendiri-sendiri buat mencapai tujuannya sendiri.”
Fokus utama sebuah hubungan kan gimana orang bisa menuhin perasaan partnernya, bukan gimana caranya mereka menuhin standard relationship yang ada. Yaa intinya, jangan sampe karena menuhin standard relationship timeline hubungan lo sama doi jadi toxic.
Terus kenapa ada pressure sosial kalo pasangan harus ngikutin relationship timeline?
Menurut Chavez, tekanan sosial seseorang harus menikah dan punya anak diakari pada cis-hetero-patriarki dan adanya asumsi kalo semua orang emang harus monogami.
Ini gue kasih kalimat gampangnya ya, seorang laki-laki dan perempuan harus jadi ‘satu’ dan ngabisin sisa hidup mereka bareng-bareng dan bikin anak. Intinya orang-orang punya kebutuhan prokreasi atau hubungan suami-istri harus punya keturunan buat nerusin generasi.
Yaa walaupun kalo lo liat sekarang, anak-anak Gen Z yang banyak free child. Mereka dianggap ngelawan arus tekanan sosial dari jalur tradisional.

Tekanan sosial ini bisa nyakitin hubungan seseorang gak?
Ya coba lo bayangin aja ada tekanan dari keluarga atau dari teman buat bikin hubungan yang KATA mereka ideal. Ini urusannya udah sama stereotip. Kalo kata Chavez, timeline relationship ini lama-lama jadi nyiptain harapan yang nggak realistis dan bikin orang selalu ngerasa nggak cukup.
Ya coba lo bayangin aja, udah pacaran lama-lama tapi ada berekspektasi buat nikah. Udah nikah heboh-heboh, tapi katanya nggak lengkap kalo nggak punya anak. Udah punya anak 1, katanya kurang. Dan seterusnya…
Kalo salah satu fase itu ada yang kelewat, pasti langsung ngerasa ‘kurang’ hubungannya jadi nggak ‘sempurna’.

Ada supervisor pekerja sosial lain yang bernama, Neathery Falchuk, dia bilang “fokus yang berlebihan sama pencapaian hubungan jelas mengganggu hubungan tersebut. Orang jadi nggak tau apa yang benar-benar mereka butuhkan dan inginkan dalam suatu hubungan.”
Ya karena, bukannya ngebangun hubungan yang aman, menyenangkan, penuh kasih sayang, malah jadi hubungan yang penuh kebencian dan stress.
So, ya. Emang ada stereotip di masyarakat kalo setiap orang harus ngikutin relationship timeline. Harus nikah, harus punya anak, harus punya cucu. Tapi balik lagi, semua tergantung sama kondisi dan latar belakang kita ygy.
Inget, nggak ada yang maksa lo buat ngikutin timeline. Ya, kecuali tetangga julid.